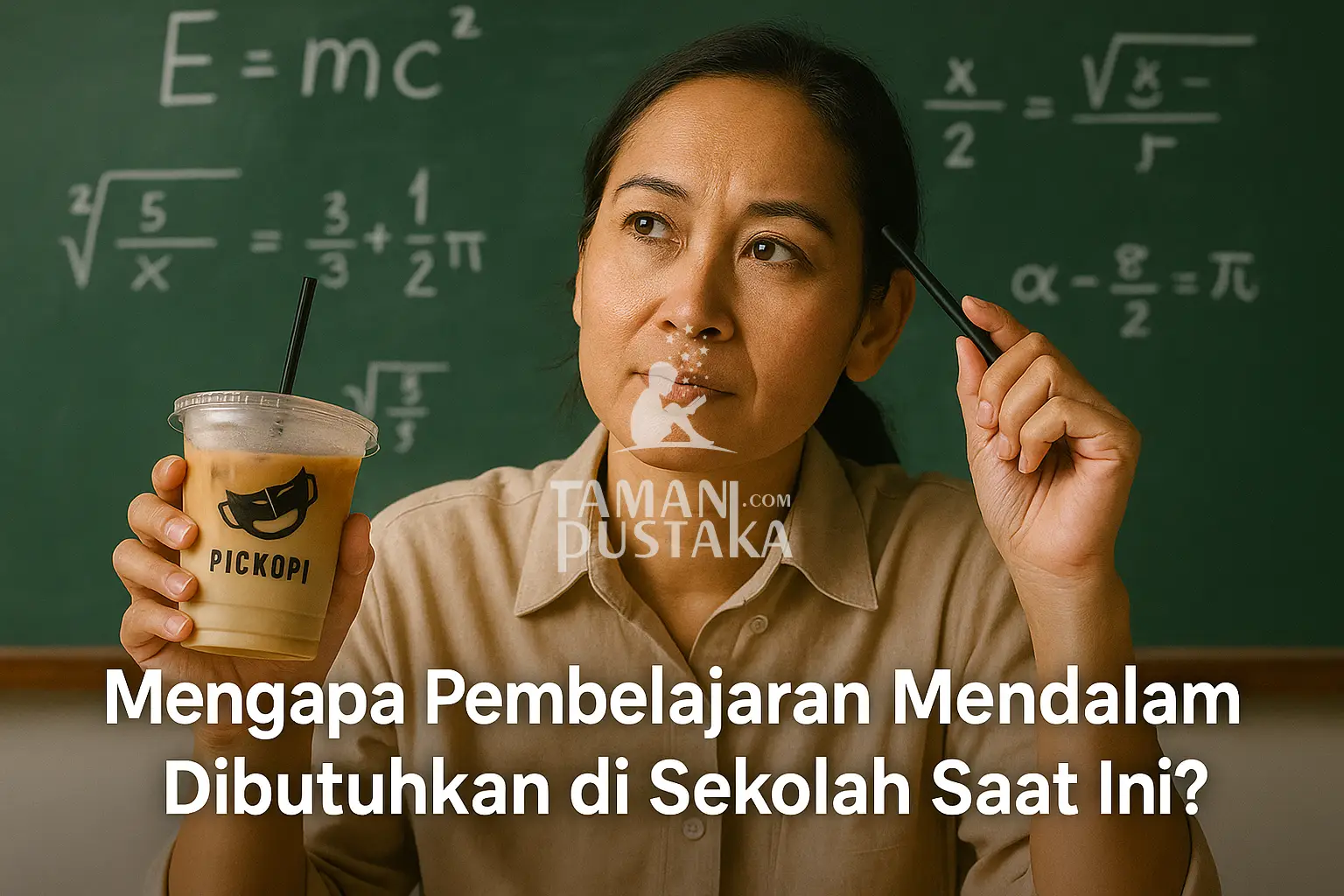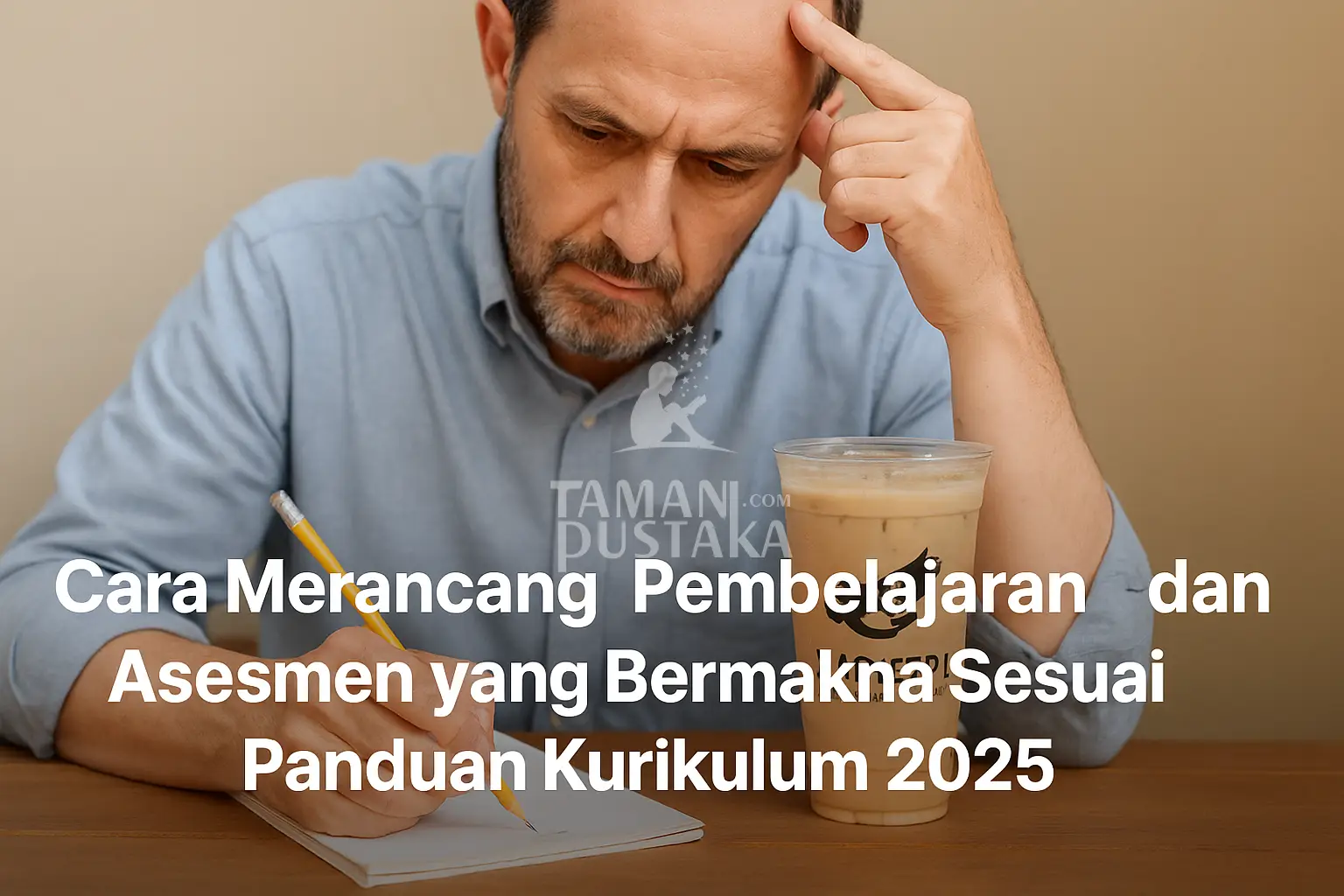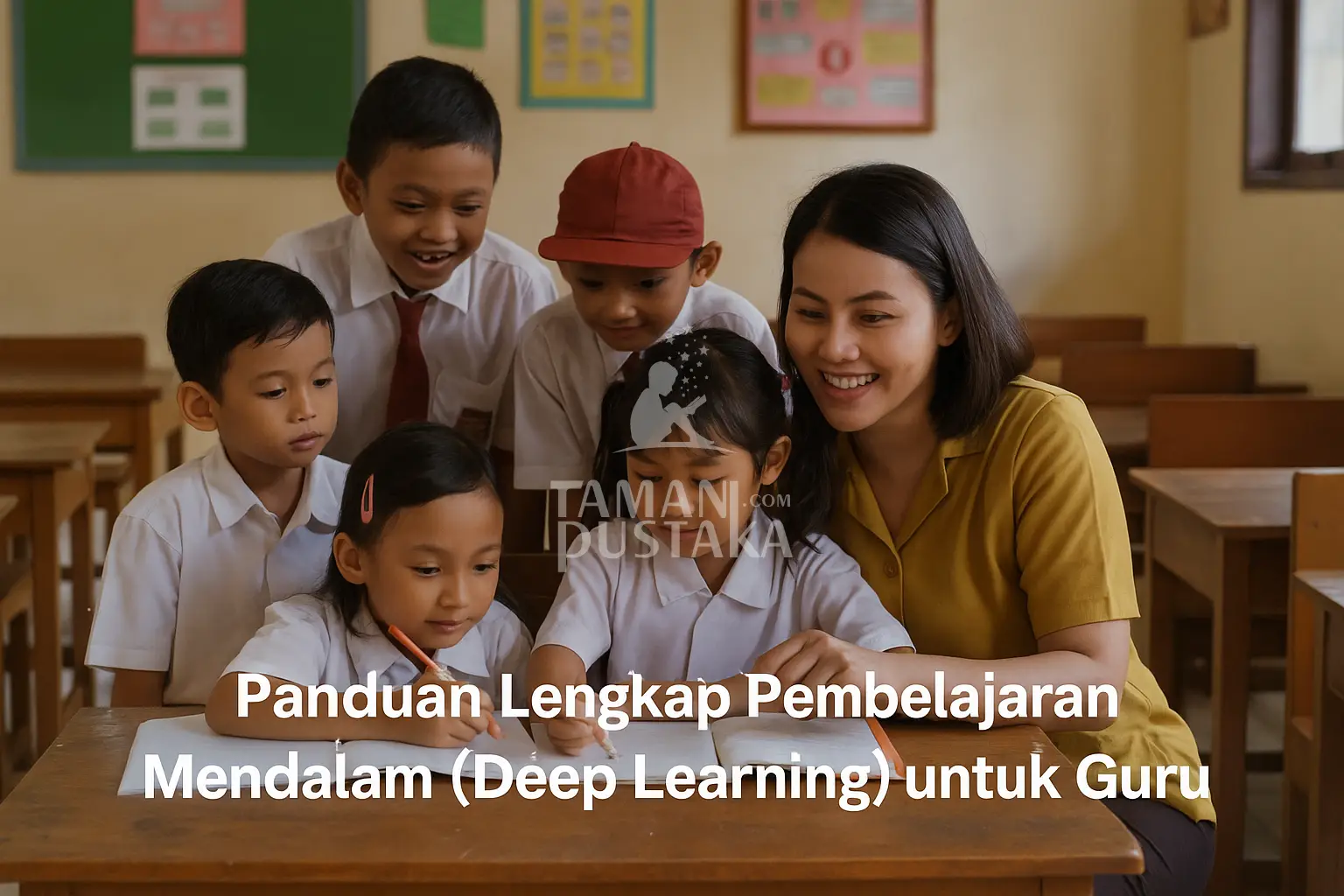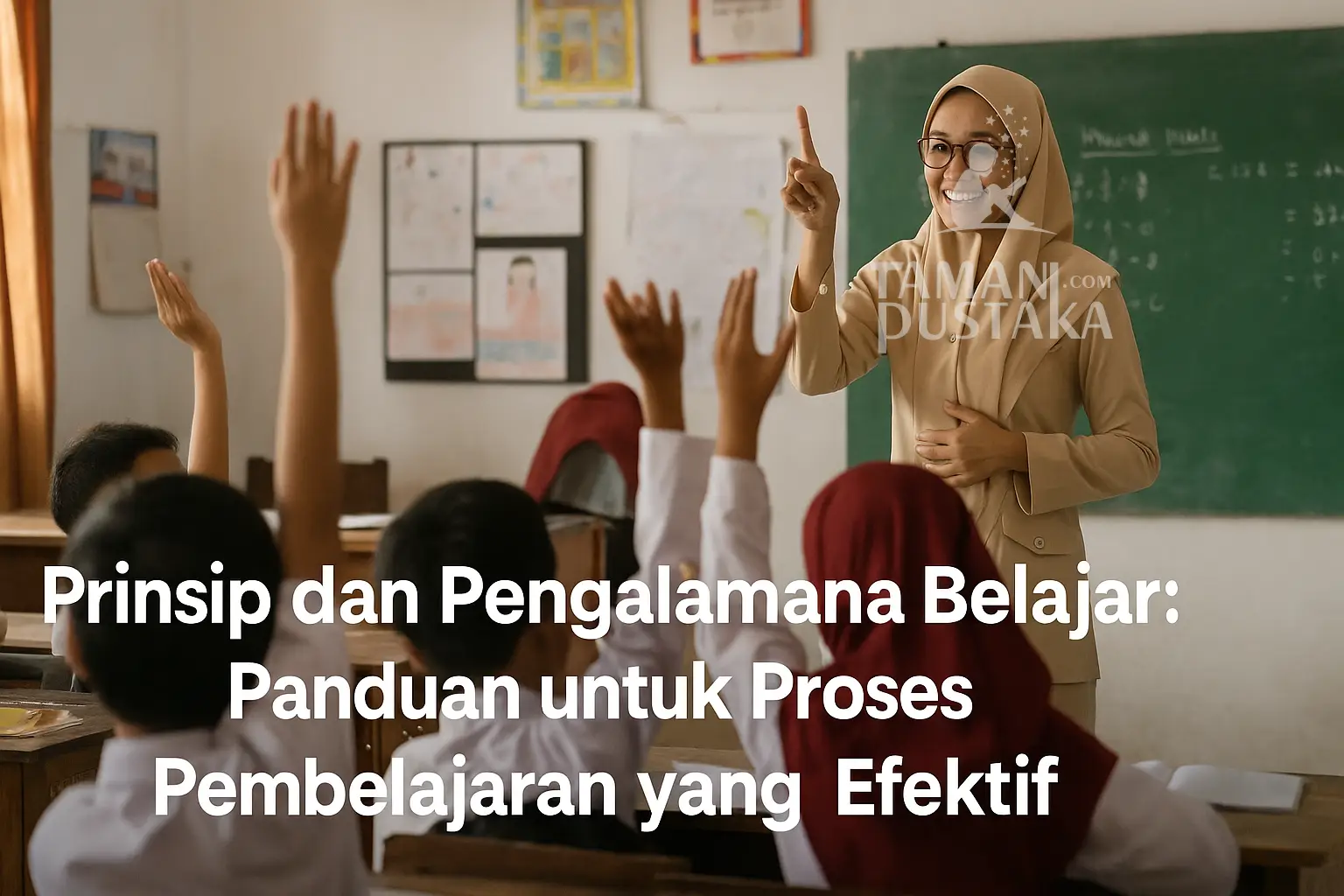TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Mengenal Taksonomi SOLO Dan Bloom Dalam Pembelajaran Mendalam
24 - Juli - 2025 99 Share :Pelajari perbedaan taksonomi SOLO dan Bloom untuk memahami level kognitif dalam pembelajaran mendalam.
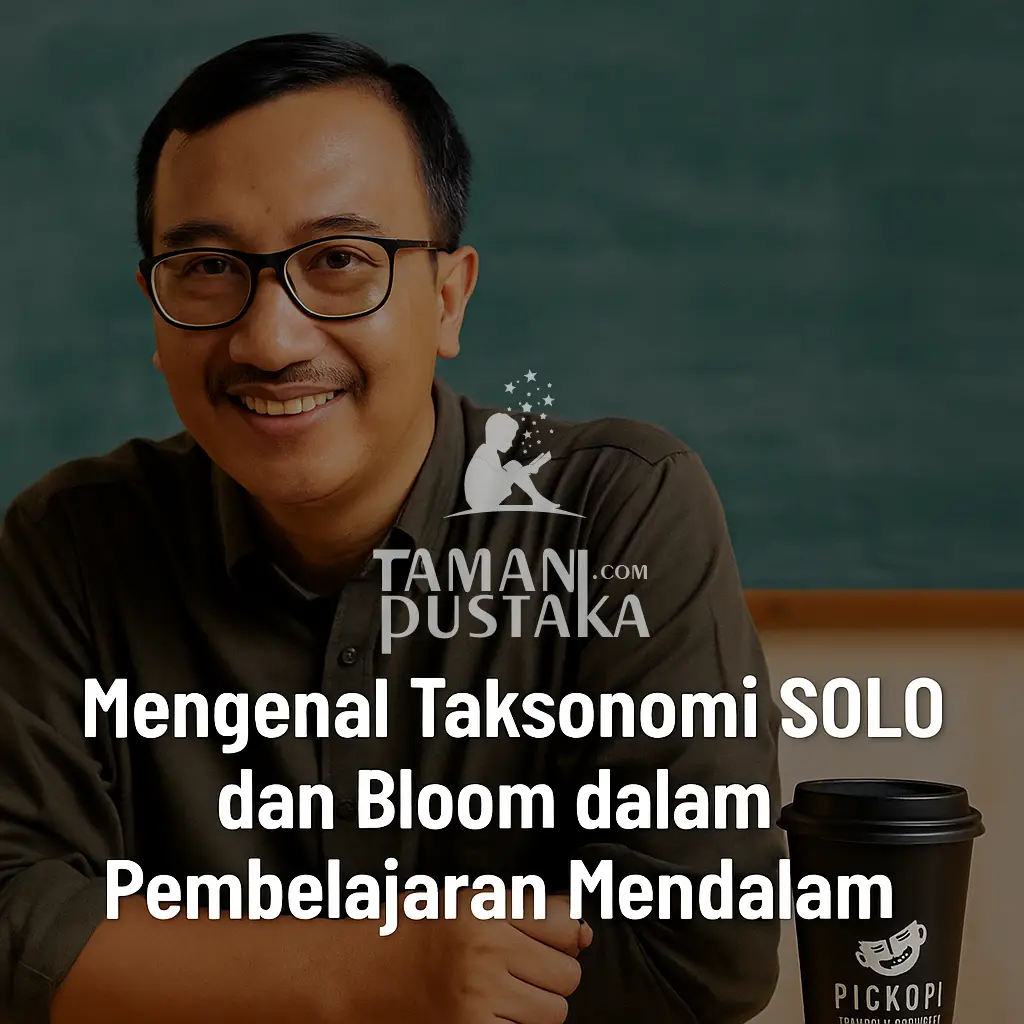
Pernah nggak sih, saat mengajar atau belajar, kita bingung menentukan apakah siswa sudah benar-benar memahami materi? Nah, di sinilah taksonomi kognitif berperan penting. Dua yang paling populer adalah Taksonomi SOLO dan Bloom. Artikel ini cocok banget buat guru, kepala sekolah, atau murid yang penasaran kenapa sih belajar itu nggak cuma soal hapalan. Yuk kita gali bareng!
1. Apa Itu Taksonomi SOLO?
Pernah merasa siswa sudah belajar, tapi pas ditanya jawabannya malah melenceng jauh? Nah, Taksonomi SOLO bisa jadi kunci buat memahami kenapa itu bisa terjadi. SOLO adalah singkatan dari Structure of Observed Learning Outcomes, yang artinya struktur hasil belajar yang bisa diamati. Taksonomi ini dikembangkan oleh dua pakar pendidikan, John Biggs dan Kevin Collis, sekitar tahun 1982. Jadi, ini bukan teori asal-asalan ya—sudah digunakan secara luas di dunia pendidikan!
Dengan pendekatan berbasis pengamatan nyata, SOLO membantu guru, kepala sekolah, bahkan siswa itu sendiri untuk melihat sejauh mana pemahaman yang telah dibangun. Bukan cuma soal benar atau salah, tapi seberapa dalam seseorang memahami sebuah konsep. Ibaratnya, bukan cuma tahu permukaannya, tapi juga ngerti sampai ke akarnya.
Ada lima level dalam Taksonomi SOLO. Masing-masing menunjukkan tahapan perkembangan pemahaman siswa, dari yang masih bingung sampai yang sudah bisa berpikir kritis dan kreatif. Yuk, kita lihat satu per satu:
- Pre-structural: Di tahap ini, siswa belum memahami materi sama sekali. Jawaban mereka bisa melenceng jauh—kadang malah jawabannya bikin guru garuk-garuk kepala.
- Uni-structural: Mulai muncul pemahaman, tapi masih sebatas satu informasi atau ide saja. Ibaratnya, baru dapat satu potong puzzle.
- Multi-structural: Siswa tahu beberapa aspek, tapi belum bisa menghubungkannya. Puzzle-nya sudah banyak, tapi belum disusun jadi gambar utuh.
- Relational: Di sini mulai mantap! Siswa bisa menghubungkan berbagai ide dan membentuk pemahaman yang utuh. Puzzle-nya sudah jadi satu gambar.
- Extended Abstract: Nah ini dia level “dewa”-nya. Siswa nggak cuma paham, tapi bisa mengembangkan dan menerapkan pemahamannya ke situasi baru. Kreatif banget!
Bisa dibilang, Taksonomi SOLO itu kayak naik tangga pemahaman. Semakin tinggi tangganya, semakin luas dan dalam cara berpikir siswa. Guru yang paham ini bisa lebih bijak dalam memberi tugas atau pertanyaan. Nggak semua anak harus langsung loncat ke level tertinggi, kan? Yang penting prosesnya terus naik, meski pelan-pelan.
Yang keren dari pendekatan ini adalah: kita jadi lebih fokus ke cara siswa berpikir, bukan sekadar hasilnya. Dan buat kamu yang guru atau kepala sekolah, ini bisa jadi alat bantu refleksi juga lho—apakah pembelajaran yang kita berikan sudah menuntun siswa naik tangga pemahaman itu?
Fun fact: Banyak sekolah di luar negeri mulai meninggalkan cara penilaian kuno dan beralih ke model SOLO karena dianggap lebih manusiawi dan realistis. Menarik, kan?
2. Mengenal Taksonomi Bloom
Kalau kamu guru atau siswa yang sering bergelut dengan RPP, tujuan pembelajaran, atau soal ujian—pasti nama Bloom nggak asing lagi. Yap, Taksonomi Bloom ini sudah seperti sahabat lama dunia pendidikan. Diciptakan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956, dan kemudian diperbarui oleh Anderson dan Krathwohl tahun 2001, taksonomi ini jadi acuan utama dalam menyusun tujuan pembelajaran yang berjenjang dan masuk akal. Bukan cuma teori jadul, tapi masih relevan banget sampai sekarang!
Bloom membagi proses berpikir menjadi enam tingkatan, dari yang paling dasar (cocok untuk siswa baru mulai belajar) sampai yang paling tinggi (cocok buat bikin proyek keren atau skripsi). Nah, ini dia urutannya:
- Mengingat: Tahap awal yang fokus pada kemampuan menghafal. Nama presiden, rumus matematika, atau definisi? Ini tempatnya. Cocok buat quiz cepat atau tebak-tebakan di kelas.
- Memahami: Di sini siswa sudah bisa menjelaskan ulang dengan kata sendiri. Misalnya, ngerti kenapa 1+1 = 2, bukan cuma hafal jawabannya.
- Menerapkan: Nah, ini sudah mulai action! Ilmu yang dipelajari dipakai buat menyelesaikan soal, tugas, atau masalah nyata di sekitar. Misal, bikin poster hemat air berdasarkan materi IPA.
- Menganalisis: Di tahap ini, siswa diajak mikir lebih dalam. Misalnya, membandingkan dua cerita, atau menemukan kelemahan dalam argumen. Seru kayak jadi detektif literasi!
- Mengevaluasi: Ini level yang butuh logika dan penilaian. Siswa diajak menentukan pilihan terbaik dari beberapa opsi, dan menjelaskan alasannya. Cocok banget buat latihan debat atau diskusi kelas.
- Mencipta: Level tertinggi! Siswa membuat sesuatu yang orisinal, entah itu tulisan, karya seni, eksperimen, atau aplikasi. Di sini, mereka bukan cuma belajar... tapi benar-benar berkarya!
Dengan memahami taksonomi Bloom, guru bisa menyusun pertanyaan atau tugas sesuai kebutuhan. Mau yang ringan untuk pemanasan? Pakai level “Mengingat” atau “Memahami”. Mau yang bikin siswa mikir dan terlibat aktif? Gas ke “Menganalisis” sampai “Mencipta”. Semua tinggal diatur sesuai tujuan pembelajaran.
Satu hal yang bikin Bloom spesial adalah fleksibilitasnya. Taksonomi ini bisa dipakai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Bahkan, kalau kamu suka nge-game pun bisa nerapin taksonomi ini: dari sekadar ingat kontrol tombol, sampai menciptakan strategi menang ala pro player!
Di dunia pendidikan, taksonomi ini juga bantu kita untuk lebih adil dalam menilai. Kita bisa memastikan bahwa siswa nggak dinilai hanya dari hapalan, tapi juga dari cara mereka memahami, menerapkan, sampai berkreasi.
Tips praktis: Saat menyusun soal atau tugas, coba tanyakan pada diri sendiri: "Soal ini menguji siswa di level mana ya?" Kalau semua soal cuma minta definisi, bisa jadi kelas kita butuh variasi. Jangan-jangan murid sudah siap ke level lebih tinggi tapi kita masih kasih soal yang... ya gitu-gitu aja.
Jadi, yuk mulai terapkan Taksonomi Bloom di kelas! Nggak harus langsung ke level “mencipta” kok, tapi setidaknya kita punya peta berpikir yang jelas. Karena belajar itu bukan sprint hafalan, tapi maraton pemahaman.
3. Perbandingan Taksonomi SOLO dan Bloom
Kita sudah bahas Taksonomi SOLO dan Bloom secara terpisah. Tapi sekarang pertanyaannya, "Kalau dua-duanya bagus, mending pakai yang mana dong?" Nah, ini dia serunya—meskipun sama-sama bicara tentang kemampuan berpikir, ternyata keduanya punya pendekatan yang berbeda tapi saling melengkapi. Ibarat duet guru dan wali kelas, satu ngajarin materi, satu jaga ritme belajar.
Supaya lebih mudah, yuk kita lihat perbedaan utamanya dalam tabel mini di bawah ini:
- Fokus: Taksonomi SOLO fokus pada *kedalaman pemahaman*. Dia melihat bagaimana siswa berkembang dari belum tahu apa-apa sampai bisa menciptakan makna baru. Sementara itu, Bloom lebih memperhatikan jenis aktivitas berpikir—dari mengingat, memahami, sampai mencipta. Jadi, SOLO lebih ke arah "seberapa dalam kamu mikir", sedangkan Bloom "kamu lagi mikir tipe apa nih?"
- Struktur: SOLO punya alur yang lebih linear—seperti anak tangga yang harus dilalui satu per satu. Bloom bersifat hirarkis, mirip piramida dari yang dasar (mengingat) hingga puncaknya (mencipta). Dua-duanya punya level, tapi struktur pikirannya beda cara naiknya.
- Penggunaan: SOLO paling cocok dipakai saat guru ingin mengevaluasi pemahaman siswa secara menyeluruh, terutama untuk penilaian formatif (proses belajar, bukan hasil akhir). Sedangkan Bloom sering digunakan sebagai panduan untuk menyusun tujuan pembelajaran, indikator, atau menyusun soal ujian. Misalnya saat bikin RPP, Bloom jadi langganan muncul tuh!
Yang menarik, meski pendekatannya beda, dua taksonomi ini bisa banget dipakai barengan. Iya, betul! Gabungkan saja—misalnya, gunakan Taksonomi Bloom untuk merancang tujuan pembelajaran, lalu gunakan SOLO untuk menilai seberapa dalam siswa memahami dan mengolah informasi itu.
Contohnya begini: kamu ingin siswa “menganalisis” (level tinggi di Bloom). Nah, kamu bisa lihat lewat kacamata SOLO apakah mereka masih sekadar menyebut aspek-aspek (multi-structural) atau sudah bisa menghubungkan semua ide menjadi satu kesimpulan utuh (relational). Mantap, kan?
Jadi, bukannya pilih SOLO *atau* Bloom, tapi kenapa nggak pakai dua-duanya? Dengan kombinasi ini, guru bisa punya alat super komplit untuk merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran secara mendalam. Bukan cuma bikin siswa pinter jawab soal, tapi juga bantu mereka jadi pemikir hebat di masa depan.
Catatan akhir buat para guru: Jangan takut mencoba pendekatan baru. Dunia pendidikan terus berkembang, dan kita—para guru, kepala sekolah, bahkan siswa—adalah bagian penting dari proses belajar yang terus hidup. SOLO dan Bloom bukan sekadar teori, tapi bisa jadi sahabat akrab di ruang kelas. ????
4. Manfaat dalam Pembelajaran Mendalam
Jadi, kenapa sih guru (dan bahkan siswa) perlu kenalan dekat dengan Taksonomi SOLO dan Bloom? Karena keduanya bukan sekadar teori di atas kertas. Kalau dipahami dan diterapkan dengan baik, dampaknya luar biasa! Bukan hanya untuk nilai siswa, tapi untuk seluruh proses belajar yang lebih hidup dan bermakna.
Berikut ini beberapa manfaat nyata yang bisa kamu rasakan di kelas jika mulai menerapkan dua taksonomi ini:
- Siswa berpikir lebih kritis dan kreatif: Mereka nggak cuma hafal, tapi bisa menganalisis, menyusun ide, bahkan menciptakan sesuatu. Serasa punya laboratorium otak mini di kepala mereka!
- Pembelajaran jadi lebih terstruktur dan berkelanjutan: Guru bisa menyusun materi dan aktivitas belajar dari tahap paling dasar ke paling tinggi. Nggak loncat-loncat kayak naik eskalator rusak.
- Evaluasi lebih adil dan bermakna: Penilaian nggak cuma soal benar atau salah. Tapi juga menilai proses berpikir, usaha, dan cara siswa menyampaikan ide. Semua jadi terasa lebih manusiawi.
- Guru bisa refleksi diri: Kadang kita juga perlu berhenti sejenak dan tanya, "Materi yang saya ajarkan ini udah bikin siswa mikir lebih dalam belum, ya?" Nah, Bloom dan SOLO bisa jadi kaca pembesar buat evaluasi gaya mengajar kita sendiri.
Kalau boleh jujur, dua taksonomi ini tuh ibarat GPS buat pembelajaran. Mereka membantu kita—guru, kepala sekolah, dan siswa—untuk tahu di mana posisi kita sekarang, dan ke arah mana kita akan berkembang. Mau ke “mengingat” atau “mencipta”? Mau sekadar tahu permukaan atau menyelami makna? Semua bisa diukur dan ditata.
Dan yang paling penting, pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa merasa dihargai proses berpikirnya, bukan cuma hasil akhirnya. Guru pun lebih punya pegangan saat menyusun kegiatan belajar yang menantang, tapi tetap sesuai kemampuan anak-anak.
Singkatnya? Taksonomi Bloom dan SOLO itu bukan teori susah. Mereka adalah alat bantu belajar yang kalau dipakai dengan bijak, bisa bikin kelas jadi tempat tumbuh yang luar biasa. Bukan sekadar tempat menyalin catatan, tapi ruang eksplorasi dan petualangan pikiran!
Jadi yuk, mulai dari sekarang, kita ubah mindset pembelajaran. Bukan cuma ‘ayo cepat selesai’, tapi jadi ‘ayo lebih dalam dan bermakna’. Karena dunia hari ini nggak butuh siswa yang hafal segalanya, tapi yang bisa berpikir jernih, kreatif, dan solutif.

Aristo Bharata
Founder tamanpustaka.com & guru di UPTD SPF SDN Sekarputih 1 Kecamatan Tegalampel Bondowoso